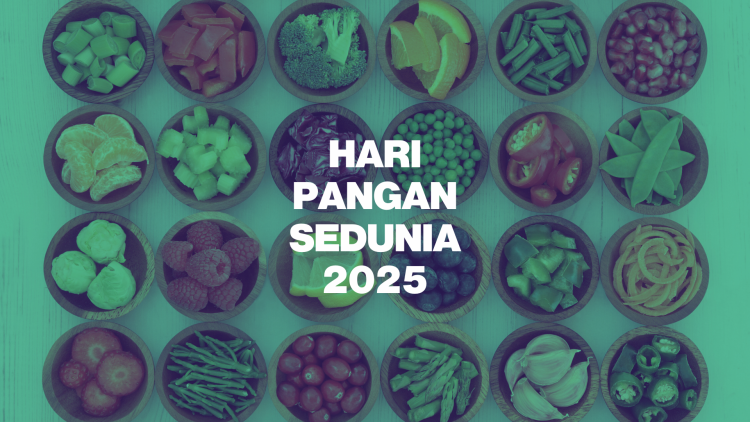
Schoolmedia News Jakarta == Setiap tanggal 16 Oktober, dunia memperingati Hari Pangan Sedunia sebagai momentum refleksi terhadap hak asasi manusia paling mendasar: hak atas pangan yang cukup, sehat, dan bergizi. Namun bagi Indonesia, peringatan tahun ini justru menjadi cermin buram dari kegagalan negara dalam memenuhi mandat konstitusionalnya.
Alih-alih menegakkan kedaulatan pangan, arah kebijakan nasional justru kian terseret dalam arus komersialisasi, militerisasi, dan ketergantungan terhadap korporasi besar.
Dalam pernyataan yang dirilis bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, Koalisi PACUAN (Pangan untuk Keadilan, Ubiquitas, dan Akses Nasional) yang terdiri atas ICW, Solidaritas Perempuan, FIAN Indonesia, Pantau Gambut, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil, menegaskan bahwa Indonesia kini berada di bawah cengkeraman rezim pangan korporat.
Sejak FAO menetapkan World Food Day pada 1979, narasi global yang mengiringinya lebih menonjolkan konsep “ketahanan pangan†ketimbang “kedaulatan panganâ€. Perbedaan keduanya sangat mendasar.
Ketahanan pangan hanya berfokus pada ketersediaan dan akses, sementara kedaulatan pangan menekankan kendali rakyat atas sumber-sumber pangan mereka sendiri: tanah, benih, air, dan pengetahuan lokal.
Indonesia, sayangnya, lebih memilih jalur pertama. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan memaknai ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseoranganâ€, dengan menautkan pemenuhannya pada mekanisme pasar. Artinya, pasar menjadi hakim tertinggi dalam menentukan harga, ketersediaan, hingga akses pangan.
“Konsep ini membuka ruang impor seluas-luasnya demi alasan efisiensi ekonomi pangan,†ujar peneliti ICW dalam rilisnya. “Impor dianggap solusi logis, padahal itu justru menggerogoti kedaulatan dan memperlemah posisi petani kecil.â€
Sementara UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta UU No. 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan praktis tak berjalan. Reforma agraria yang dijanjikan sejak lama pun mandek.
Ketika mekanisme pasar menjadi pusat gravitasi kebijakan, korporasi pun naik ke tahta utama sistem pangan. Mereka menguasai tanah, teknologi, dan rantai pasok. Produksi pangan diubah menjadi kegiatan industri berbasis modal besar, lahan luas, dan input kimia berlebih.
“Pola ini mengulang logika Revolusi Hijau yang dulu dijanjikan menyejahterakan petani, namun justru menjerat mereka dalam kemiskinan baru,†tulis Koalisi PACUAN.
Kegagalan proyek tersebut kemudian dijadikan pembenaran untuk memperluas konsesi lahan perkebunan sawit dan karet berskala besar. Korporasi transnasional pun leluasa menancapkan kuku bisnisnya di wilayah-wilayah subur.
Kini, ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia kian dalam: 1 persen entitas menguasai lebih dari separuh tanah produktif di negeri ini. Petani kecil dan masyarakat adat tersingkir dari ruang hidupnya sendiri.
Sawit Wajah Gelap Ketimpangan Pangan
Sawit menjadi simbol paling mencolok dari wajah gelap kebijakan pangan berbasis modal.
Di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, jutaan hektar hutan adat dan kebun pangan rakyat beralih menjadi perkebunan monokultur. Sungai-sungai yang dulu menjadi sumber air dan ikan kini tercemar limbah pabrik.
“Ekspansi sawit tidak hanya menghancurkan lingkungan, tapi juga memutus akses masyarakat terhadap pangan lokal,†kata perwakilan FIAN Indonesia. “Banjir dan kekeringan menjadi bencana tahunan yang berulang.â€
Krisis pangan di Indonesia, lanjutnya, bukan karena produksi yang kurang, melainkan karena ketimpangan struktural dan korupsi tata kelola sumber daya alam. “Tanah subur dikuasai korporasi, sementara petani kecil tak lagi punya lahan untuk menanam.â€
Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dua program besar — Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Food Estate — menjadi sorotan utama kelompok masyarakat sipil.
Program MBG, yang diklaim untuk memenuhi gizi masyarakat miskin dan pelajar, disebut ICW sebagai kebijakan populis yang minim transparansi dan partisipasi publik. “Pangan dijadikan kendaraan politik, bukan hak dasar rakyat,†ujar peneliti ICW.
Koalisi Tolak MBG menemukan program ini tidak memenuhi prinsip hak atas pangan: mulai dari transparansi, mutu gizi, aksesibilitas ekonomi, hingga keadilan anggaran.
Sementara proyek Food Estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, hingga Merauke disebut telah memperparah krisis ekologis dan sosial.
FIAN Indonesia mencatat tiga bentuk pelanggaran negara: gagal menghormati, gagal melindungi, dan gagal memenuhi hak atas pangan. Lahan gambut yang dibuka untuk proyek pangan skala besar justru dibiarkan terlantar.
Pantau Gambut bahkan menyebut program ini sebagai ancaman “bom karbonâ€, karena pembukaan lahan di eks Proyek Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah terus memicu kebakaran dan pelepasan emisi masif.
“Food Estate bukan solusi krisis pangan, melainkan sumber krisis baru,†tegas Koalisi PACUAN.
Kritik tajam juga diarahkan pada meningkatnya peran militer dalam pengelolaan sektor pangan. Sejumlah proyek seperti PT Agrinas Palma Nusantara dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) disebut melibatkan unsur militer tanpa akuntabilitas publik yang jelas.
“Pangan dijadikan urusan pertahanan nasional. Ini kekeliruan berpikir yang fatal,†kata ICW.
Kasus PT Agrinas Palma Nusantara menjadi contoh nyata. Setelah mengambil alih kebun eks PT Duta Palma, perusahaan yang berafiliasi dengan militer ini gagal memulihkan hak buruh dan hak masyarakat atas pangan.
Di lapangan, Satgas PKH kerap memicu konflik agraria karena pengambilalihan lahan dilakukan secara sepihak dan represif.
Proyek MBG pun tak luput dari potensi konflik kepentingan. Meski belum muncul kasus korupsi, tata kelola yang tertutup dinilai membuka peluang rente politik. “Pola lama terus berulang: pangan menjadi ladang basah kekuasaan,†tulis ICW, merujuk pada sejarah kasus korupsi impor sapi (2013) hingga bansos beras (2020).
Perempuan dan Ketimpangan Pangan
Dalam sistem pangan yang semakin korporatis, perempuan menjadi kelompok paling terdampak. Mereka kehilangan peran penting sebagai penjaga pengetahuan pangan lokal.
“Pembangunan pangan yang maskulin dan militeristik mengabaikan peran perempuan,†ujar Solidaritas Perempuan.
UU Cipta Kerja, yang melonggarkan impor pangan, memperburuk situasi ini. Ketika pasar dibuka lebar bagi produk asing, perempuan petani dan nelayan kehilangan ruang hidup.
Padahal di banyak daerah, perempuan menjadi garda depan ketahanan pangan lokal. Di Sumba, perempuan mengolah ubi beracun menjadi pangan alternatif saat musim paceklik. Di Kulon Progo, mereka mengembangkan pertanian organik dan benih lokal untuk melawan sistem pertanian kimiawi.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, 3.624 perempuan dari 57 desa mengalami penindasan dan pemiskinan akibat proyek-proyek pangan berskala besar (Catahu Solidaritas Perempuan 2025).
“Krisis pangan juga adalah krisis gender,†tegas koalisi tersebut. “Selama negara tidak mengakui perempuan sebagai pemangku hak atas pangan, ketimpangan ini akan terus melebar.â€
Di tingkat global, ancaman lain datang dari liberalisasi pasar dan perjanjian dagang seperti Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I–EU CEPA).
Perjanjian ini menekan Indonesia agar bergabung dengan Konvensi UPOV 1991, yang memberi hak monopoli atas benih kepada korporasi. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menegaskan hak petani untuk menyimpan dan menukar benih.
“Jika Indonesia tunduk pada UPOV, petani akan kehilangan kendali atas benih. Ini sama saja dengan mencabut akar kedaulatan pangan,†ujar ICW.
Kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang membebaskan tarif impor produk pertanian juga dikhawatirkan memperlemah petani kecil. Produk pangan murah impor akan membanjiri pasar lokal, menekan harga hasil tani dalam negeri.
“Kontradiksi mencolok muncul di sini,†kata peneliti FIAN. “Pemerintah berbicara swasembada, tapi kebijakannya membuka pintu selebar-lebarnya untuk impor.â€
Seruan Rebut Kembali Hak Rakyat
Bagi Koalisi PACUAN, Hari Pangan Sedunia bukan sekadar seremoni, tetapi seruan untuk merebut kembali hak rakyat atas sumber kehidupan. Mereka mengajukan delapan tuntutan konkret kepada pemerintah:
-
Menegakkan kedaulatan pangan melalui reforma agraria, perlindungan lingkungan, dan dukungan terhadap sistem pangan lokal;
-
Menghentikan militerisasi sektor pangan;
-
Mengevaluasi dan menghentikan proyek MBG dan Food Estate;
-
Menjamin transparansi dan akuntabilitas program pangan nasional;
-
Menegakkan hak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat atas tanah dan sumber agraria;
-
Memastikan keterlibatan produsen pangan kecil dalam perumusan kebijakan;
-
Menindak praktik korupsi dan konflik kepentingan dalam tata kelola pangan;
-
Menghentikan liberalisasi pertanian dan melindungi kedaulatan pangan lokal.
Krisis pangan yang melanda dunia — termasuk Indonesia — sejatinya bukan sekadar soal kurangnya makanan. Masalah utamanya adalah siapa yang menguasai tanah, benih, dan kebijakan pangan itu sendiri.
Selama pangan diperlakukan sebagai komoditas politik, rakyat akan terus lapar — bukan karena gagal menanam, tetapi karena haknya dirampas.
“Peringatan Hari Pangan Sedunia seharusnya menjadi peringatan keras bagi negara,†tulis ICW dalam penutup siaran persnya. “Bahwa kedaulatan pangan tidak akan lahir dari proyek dan jargon, melainkan dari keberpihakan nyata pada rakyat yang menanam, memanen, dan menjaga bumi tempat kita hidup.â€
Tim Schoolmedia







Tinggalkan Komentar